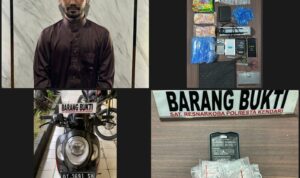SOROTANSULTRA.COM | KONAWE – banyak daerah, praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh perusahaan kerap berhenti pada level seremonial—sekadar simbol kepedulian, bukan perwujudan keadilan. Ini yang kami sebut sebagai “CSR kosmetik” : tampak indah di permukaan, tetapi kosong secara substansi. Di balik laporan-laporan korporat yang penuh angka dan foto kegiatan, masih banyak warga—terutama petani dan komunitas adat—yang kehilangan hak atas tanah, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Padahal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.
Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini adalah mandat yang tidak dapat dinegosiasikan. Namun, di tengah kenyataan sosial dan kebijakan daerah, hak ini kerap diabaikan, bahkan oleh produk hukum yang semestinya melindungi warga.
Salah satu bentuk pengabaian itu tampak dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang CSR. Banyak regulasi CSR daerah tidak disusun dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal, CSR bukan semata program pembangunan fisik, melainkan juga bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas usaha mereka.
Tanpa perspektif HAM, regulasi CSR di tingkat daerah cenderung mengakomodasi kepentingan korporasi alih-alih memperkuat posisi masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan CSR sering kali tidak menyentuh akar persoalan struktural, seperti pencemaran lingkungan, konflik agraria, atau hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah petani. Mereka bukan hanya kehilangan lahan akibat ekspansi industri, tapi juga akses terhadap air dan tanah subur. Hak petani atas sumber daya produksi dan lingkungan yang sehat kerap dikorbankan demi investasi. Padahal, bagi petani, tanah bukan sekadar alat produksi, melainkan bagian dari kehidupan, budaya, dan identitas. Ketika air tercemar, lahan rusak, dan suara petani diabaikan, maka kita sedang menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk yang sangat nyata.
Kami di PoskoHAM memandang bahwa hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin dan memenuhi HAM warganya. Ketika Perda tentang CSR tidak memasukkan prinsip-prinsip HAM—seperti partisipasi bermakna, transparansi, non-diskriminasi, dan akses terhadap pemulihan—maka regulasi itu menjadi tumpul dalam menjawab persoalan di lapangan.
Hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak dasar yang menopang pemenuhan hak lainnya, termasuk hak atas kesehatan, pangan, air bersih, dan kehidupan yang layak. Ketika lingkungan rusak akibat aktivitas korporasi, dan negara melalui pemerintah daerah tidak menghadirkan regulasi yang kuat dan adil, maka hak-hak masyarakat menjadi korban. Petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang pertama terkena dampak, dan terakhir mendapat perlindungan.
Oleh karena itu, kami mendesak agar seluruh perencanaan regulasi daerah, khususnya yang mengatur CSR dan pengelolaan lingkungan, wajib disusun dengan merujuk pada Undang-Undang HAM. Regulasi tidak boleh lagi disusun dalam ruang hampa nilai. Ia harus menjawab kebutuhan perlindungan hak, keadilan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa memasukkan pertimbangan HAM dalam regulasi daerah, kita sedang membiarkan perusahaan bebas bertindak tanpa kontrol, dan membiarkan masyarakat terus menanggung dampaknya tanpa perlindungan. Sudah waktunya pemerintah daerah memposisikan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab hak asasi, bukan sekadar formalitas laporan tahunan.
Perjuangan melindungi lingkungan dan hak-hak warga adalah perjuangan untuk keadilan yang sesungguhnya. Regulasi yang tidak memuat HAM dalam naskahnya, akan melahirkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
Sebagai Ketua PoskoHAM, saya memandang bahwa salah satu tantangan besar dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di tingkat lokal adalah lemahnya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Padahal, potensi dana CSR sangat besar jika dikelola secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga.
Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjamin hak dasar warga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka ini, kepala daerah—khususnya bupati—memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengarahkan penggunaan dana CSR secara akuntabel dan tepat sasaran.
Selain itu, Peraturan Bupati sebagai turunan Perda yang mengatur CSR semestinya juga tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen nyata pemenuhan HAM. Isinya harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, petani, dan masyarakat miskin. CSR harus diarahkan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, hingga pemulihan lingkungan.
Sudah waktunya pemerintah daerah tidak hanya menjadi fasilitator antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menjadi pengarah dan pengawas pelaksanaan CSR agar selaras dengan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip HAM. Perlu ada forum komunikasi rutin, basis data kebutuhan warga, serta sistem pelaporan yang transparan kepada publik.
Kami di PoskoHAM mendorong semua kepala daerah untuk menjadikan Peraturan Bupati tentang CSR sebagai alat transformasi sosial. Tidak cukup hanya dengan slogan “berbasis masyarakat”, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan kebijakan pembangunan.
Menolak CSR kosmetik bukan berarti menolak investasi, tetapi menuntut keadilan. Kita butuh CSR yang berdampak, bukan yang sekadar dipajang dalam laporan tahunan perusahaan. Kita butuh suara HAM yang lahir dari ladang, sungai, dan tanah yang ingin terus hidup.(*)
Oleh : Jumran, S.IP, Ketua PoskoHAM Indonesia